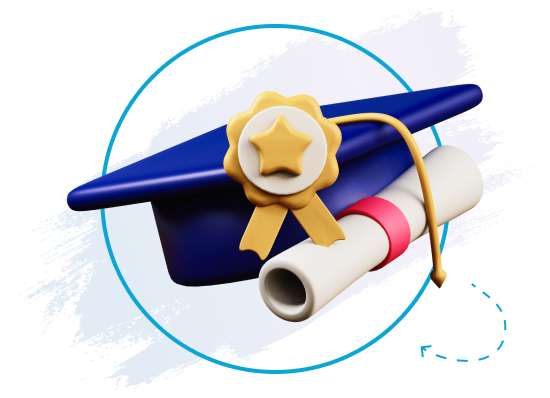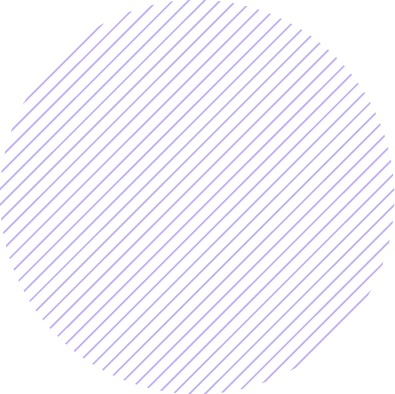Ketika Kita Ingin Bersekolah
Perjalanan hari di tahun 2007 ini akan segera berakhir dengan membawa beberapa permasalahan yang harus diselesaikan pada lembaran tahun berikutnya. Dan kita hanya bisa melakukan perenungan ââ¬â serta penyesalan ââ¬â terhadap apa yang telah kita kerjakan pada hari-hari sebelumnya. Permasalahan yang akan terus membayangi negeri ini pada awal tahun 2008 tidak terlepas dari segala persoalan mendasar yang seolah-olah ââ¬â dan kenyataanya memang benar ââ¬â begitu melekat erat di sendi-sendi masyarakat Indonesia. Permasalahan tersebut adalah tingkat kemiskinan serta keambrukan pendidikan.
Secara logika alamiah, kita bisa menarik benang merah antara kemiskinan dengan pendidikan. Dan memang pada kenyataannya titik tumpu lahirnya kemiskinan adalah kurang teraplikasinya secara nyata hasil dari proses pendidikan yang telah ada semenjak dahulu di negeri ini.
Menurut Paulo Freire, seorang pemikir pendidikan dari Brazil, tujuan dari pendidikan seyogyanya adalah memanusiakan manusia. Setiap orang tentunya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Freire tersebut. Dengan arti kata, pendidikan bertujuan untuk melahirkan generasi ââ¬â generasi yang memiliki pengetahuan, budi pekerti, berjiwa sosial, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapatkannya kepada lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan taraf hidup bersama. Tujuan mulia tersebut bila telah dipahami secara mendalam oleh setiap individu di negeri ini maka tidak akan ada lagi kesenjangan di setiap golongan masyarakat.
Sejarah Pendidikan
Kita tentunya mengenal bahwa suatu pelembagaan yang disusun secara sistematis, dilengkapi segala keseragaman mulai dari bangunan, kurikulum, baju, buku serta jurnal, serta memiliki perangkat yang berfungsi untuk mentranformasikan segala pengetahuannya kepada orang-orang yang ingin mengenal sesuatu yang belum mereka ketahui atau untuk memperdalam pengetahuan yang telah mereka ketahui sebelumnya itulah yang secara bersama dimaknai oleh masyarakat awam sebagai sekolah.
Padahal jauh sebelum adanya sekolah yang kita kenal pada saat ini, menurut Roem Topatimasang dalam bukunya Sekolah Itu Candu*, telah ada yang namanya sekolah. Tapi, sekolah pada zaman itu hanyalah sebagai tempat pengisi waktu senggang bagi anak-anak untuk menanyakan segala sesuatu yang belum mereka ketahui. Hal tersebut tidak terlepas dari pemaknaan asal kata sekolah, yaitu scolae, skhole, yang artinya mengisi waktu luang. Pada waktu itu, para orang tua menitipkan anak mereka kepada orang yang dianggap layak karena mereka merasa tidak sanggup lagi mengajarkan apa yang mereka ketahui kepada anak mereka disebabkan perkembangan keadaan sekitar yang berpengaruh terhadap pengetahuan baru yang belum mereka dapatkan kepada orang di mana mereka ber-skhole dulu. Di tempat tersebut anak-anak belajar, bermain, serta berlatih mengaplikasikan pengetahuan baru yang mereka dapatkan sampai tiba saatnya mereka untuk kembali ke rumah mengerjakan pekerjaan yang telah menunggu mereka.
Sampai pada massa akan datangnya renaisance, Johannes Amos Comenius, membuat sebuah buku yang merupakan Fons Et Origonya ilmu pengetahuan yang berisikan teori pengajaran dan dikenal dengan kitab Didactica Macna. Di dalam buku tersebut, diatur mengenai pola pengembangan bagi pendidikan pendidikan secara metodis dan tersistematis. Hal ini dikarenakan adanya keberagaman latar belakang anak serta proses pengembangan anak tersebut yang membutuhkan penanganan khusus. Di sinilah awal munculnya penjenjangan di dalam pendidikan formal di setiap negeri serta awal mula kebobrokan pendidikan yang terjadi di setiap negeri, khususnya Indonesia.
Melihat perkembangan lembaga pendidikan ( sekolah ) pada saat ini, telah terjadi suatu penafian terhadap komitmen awal dari sejarah lahirnya pendidikan di seluruh dunia. Penolakan tersistematis terhadap pendidikan pada saat ini bisa saja diminimalisir oleh setiap golongan bilamana kita paham arah atau tujuan yang ingin dicapai untuk menghadapi tantangan masa depan yang akan sangat mungkin berbeda.
ââ¬Å ââ¬Â¦.apakah kita sedang bergerak ke arah pendidikan yang diperluas dan menyusun rencana dengan gagasan bahwa perkembangan individu adalah suatu praxis, ataukah kita justru sedang menuju ke arah scolae dalam arti kata yang sebenarnya ? ââ¬Â (Deklarasi Cuernavaca 1971)
*untuk lebih jelas baca Roem Topatimasang Sekolah Itu Candu.
Pembelokan Terstruktur
Kemunculan kitab Didactica Magna tersebut menyebabkan pendidikan pada hari ini sedang mendekati proses kematian. Kita mengetahui bahwa segala aspek yang ada di dalam lingkungan pendidikan telah diseragamkan oleh pembuat kebijakan. Mereka yang ingin bersekolah diwajibkan memiliki baju seragam yang tidak seluruh masyarakat dapat memenuhinya, membeli buku-buku sekolah yang terkadang telah melewati ââ¬Å masa kadaluarsa ââ¬Å, menjalankan kurikulum yang dipaksakan untuk disamakan dengan keinginan pembuat kebijakan, memenuhi biaya sekolah yang begitu tinggi, serta mengikuti ujian yang disentralisasi tanpa mempertimbangkan kelayakan lulusannya, serta berbagai macam tuntutan yang harus ââ¬â dan memang dipaksakan ââ¬â dipenuhi oleh masyarakat di negeri ini.
Kewajiban yang akan ââ¬â dan memang ââ¬â memberatkan masyarakat tersebut tidak diimbangi dengan apa yang mereka peroleh dari lembaga pendidikan tempat mereka ââ¬Å mengadu ââ¬Å. Secara garis besar kita bisa melihat bahwa tuntutan menggunakan pakaian seragam oleh sekolah tidak menjamin mereka untuk mampu memahami apa yang telah diberikan oleh sang pendidik. Tentunya keterbatasan tersebut muncul dari pribadi sesorang untuk mengerti sesuatu, tapi hal tersebut bisa diminimalisir ketika para pendidik mampu untuk mengelaborasi seluruh keterbatasan tersebut menjadi suatu bentuk tranformasi pengetahuan yang bisa segera diaplikasikan secara nyata oleh manusia-manusia yang didik oleh mereka. Pada kenyataannya setiap murid, pelajar, siswa, bahkan mahasiswa dituntut untuk memahami segala perbuatan dari sang pendidik bukan sebaliknya para pendidik yang harus memahami manusia-manusia yang dididik olehnya.
Permasalahan pendidikan di Indonesia cukup mendapatkan respon yang baik dari pemerintah dari segi penyaluran anggaran pemerintah bagi sektor pendidikan. Hal ini dapat terlihat dari besaran persentase bagi dunia pendidikan Indonesia sebesar 20% dari APBN. Rakyat yang berada di golongan bawah tentunya sangat apresiatif terhadap ini, karena anggaran tersebut dapat memenuhi biaya pendidikan yang ditanggung oleh mereka. Ya, dengan anggaran tersebut setiap warga negara Indonesia bisa mengenyam pendidikan gratis. Ya, dengan anggaran tersebut setiap warga negara Indonesia tidak lagi akan membeli buku-buku pendidikan yang sangat amat memberatkan. Ya, dengan anggaran tersebut kita tidak akan lagi melihat anak-anak mengerjakan tugas orang tuanya di ruas jalan utama di setiap kota.
Ya, anggaran tinggal anggaran, perencanaan tinggal perencanaan. Kita hanya bisa bermimpi untuk mengenyam pendidikan yang biayanya sangat memberatkan bagi golongan mayoritas di negeri ini. Bahkan mimpi-mimpi itu pun terkadang membunuh kita dengan sendirinya.
Bertebarannya berita di koran mengenai seorang siswa yang meninggal bunuh diri karena tidak sanggup membayar uang untuk studi banding sebesar Rp. 8.000,- merupakan salah satu contoh dari biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat yang kurang mampu. Bila kita menggunakan logika dasar kita sebagai manusia, tidak sewajarnya seorang manusia mengakhiri hidup hanya karena beban Rp. 8.000,- yang memberatkan baginya, serta banyak lagi permasalahan akan kebutuhan pokok yang harus mereka penuhi. Dengan harga tersebut menghilangkan nyawanya yang oleh orang-orang kaya harga tersebut tidak akan mengurangi kekayaan mereka.
Permasalahan dasar yang bisa diambil dari contoh kasus di atas bukan hanya sebatas pada ketidakmampuan untuk memenuhi biaya kegiatan yang hanya sebagai pendukung bagi kelancaran proses pendidikan, tetapi pendidikan pada saat ini telah menghilangkan kesempatan bagi warga negara untuk mendapatkan hak mereka secara layak dengan membebankan biaya yang begitu tinggi kepada setiap warga negara. Dengan arti kata orang miskin di Indonesia dilarang untuk menikmati fasilitas negara di sektor pendidikan.
Yah, memang seperti itulah realita pendidikan di Indonesia.
Indonesia Menuju Liberalisasi Pendidikan
Capaian kerja stakehoder di negeri ini bisa dikatakan ââ¬Å hampir sempurna ââ¬Å bila sudut pandang kita melihat sejauhmana kebijakan yang telah dibuat demi kelangsungan pendidikan bagi masyarakat Indonesia dengan mengenyampingkan hak-hak warga negara yang dipelihara oleh negara. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.77 Tahun 2007 mengenai Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal di mana sektor pendidikan termasuk ke dalam Bidang Usaha yang Terbuka. Masuknya pendidikan ke Bidang Usaha terbuka ini memperlihatkan bahwa Indonesia telah meliberalisasi sistem pendidikannya. Dan Perpres ini akan semakin menyengsarakan rakyat miskin di Indonesia.
Modal asing yang akan diinvestasikan ke sektor pendidikan dibatasi sebesar 49% dan penanaman tersebut akan berlangsung lama bila kita mengacu pada Undang-Undang Penanaman Modal yang telah direvisi pada tahun 2006 lalu. Pantas atau tidaknya sektor pendidikan mendapatkan investasi langsung dari pemodal asing tentunya telah mendapatkan jawaban dari kita sendiri. Memang dalam jangka waktu dekat investsi tersebut tidak akan berimbas pada kurikulum pendidikan Indonesia. Tapi, kita tentunya tidak bisa memalingkan muka bahwa dikemudian hari kurikulum pendidikan indonesia yang telah bobrok ini akan semakin diporakporandakan oleh pemikiran-pemikiran dari para penginvestor tersebut. Dengan Perpres itu para investor akan merenggut kekayaan yang ada di Indonesia. Mereka dalam menginvestasikan uangnya tentu telah memikirkan pengembalian yang akan diterimanya. Tidak serta merta menanamkan modal tanpa ada imbalan yang sepadan ataupun melebihi apa yang ditanamkannya di negeri ini.
Pada perspektif lain kita melihat bahwa perguruan tinggi di negeri ini digiring untuk menjauh dari sentuhan anggaran pemerintah, khususnya perguruan tinggi negeri. Dasar tersebut bisa kita lihat dari munculnya Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Milik Negara yang berisikan melepas tanggungan pemerintah terhadap perguruan tinggi negeri dengan menswastakan perguruan tinggi negeri tersebut. Dengan RUU-BHMN tersebut indikasi terhadap pelepasan tanggung jawab pemerintah di sektor pendidikan semakin menguat. Hal ini bertolak belakang dengan prembule Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ââ¬Âââ¬Â¦.. untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duniaââ¬Â. Penjaminan terhadap kecerdasan seluruh masyarakat Indonesia telah dinisbikan kembali oleh pemerintah dengan segala perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan. Padahal seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, anggaran untuk pendidikan dibebankan sebesar 20% dari APBN. Di sinilah bisa kita melihat logika terbalik yang digunakan para pembuat kebijakan di negeri ini dengan melakukan pelanggaran terhadap perundang-undang di Indonesia. Dasar hukum Tertinggi telah dikalahkan oleh peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang seyogyanya menjadi penjabaran dari undang-undang tertinggi tersebut.
Wajib Belajar 9 Tahun
Di setiap emperan jalan baik di kota ataupun di desa-desa akan mudah terlihat selebaran-selebaran atau pamflet yang mengusung Wajib Belajar 9 Tahun. Pemikiran kita tentunya akan kembali pada pemaknaan akan Undang-Undang mengenai pendidikan dimana setiap waga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan dikelola bersama oleh pemerintah bersama dengan masyarakat di negeri ini. Secara harfiah, warga negara Indonesia yang berusia 6 - 15 berkewajiban untuk mendapatkan pendidikan di lembaga pendidikan formal ( sekolah ) yang telah dibangun oleh pemerintah dari swadaya masyarakat. Kewajiban ini berkaitan dengan isi prembule UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut tentunya diikuti pula dengan penguatan perundang-undangan atau peraturan yang menjelaskan sistematika dari proses tersebut. Mulai dari bagaimana proses tranformasi pengetahuan dijalankan, pembiayaan yang dibebankan sepenuhnya kepada negara, sampai kepada referensi yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang pendidikan. Kenyataannya pada saat ini kita belum melihat hal itu terjadi, namun saat ini kita kembali dililitkan pada kenyataan bahwa sekolah-sekolah hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berada di jajaran menengah ke atas dengan menisbikan kaum bawah ( orang miskin ). Indikasi tersebut bisa kita lihat bahwa Wajib Belajar 9 Tahun disertai dengan keseragaman yang harus kita penuhi dengan biaya yang sangat mahal. Jadi, Wajib Belajar 9 Tahun hanyalah sebuah fatamorgana yang dimunculkan ke permukaan oleh stakeholder negeri ini sebagai salah satu bentuk penghapusan dosa terhadap pelanggaran perundang-undangan tanpa melihat penderitaan yang dialami oleh warga negaranya dalam memenuhi tuntutan tersebut.
Ketika kita ingin bersekolah, kita dituntut untuk memiliki pakaian seragam demi kelancaran proses mengajar. Ketika kita ingin bersekolah, kita diwajibkan untuk membeli buku-buku referensi dengan harga yang jauh dari pendapatan kita per hari. Ketika kita ingin bersekolah, kita diwajibkan untuk menyamakan isi kepala kita dengan para pendidik. Ketika kita ingin bersekolah, banyak orang menutup mata. Bahkan ketika kita diwajibkan untuk bersekolah, mereka melepas tanggung jawab yang telah diamanahkan oleh rakyatnya.
Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bersama, akan digiring ke arah mana tujuan mulia pendidikan di negeri ini ?