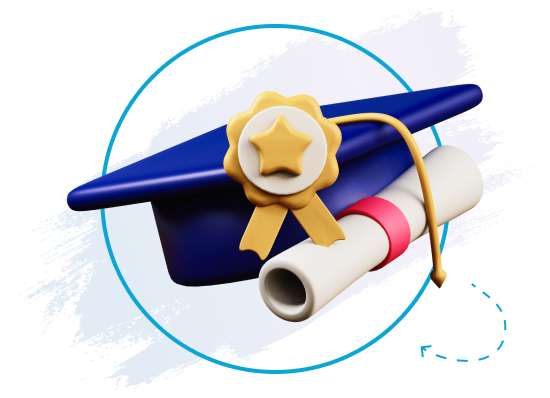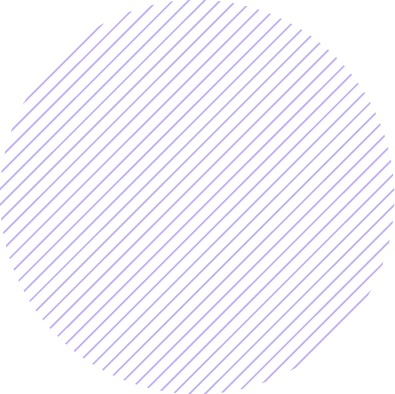Pemilu 2004 dan Implikasinya terhadap Penguatan Lembaga Legislatif Dan Pemerintahan Yang Aspratif
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Yth. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat berserta unsure Muspida Sumatera Barat
Bapak Walikota Padang
Bapak Rektor Universitas Bung Hatta
Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X
Bapak Ketua dan Anggota Yayasan Pendidikan Bung Hatta
Bapak-Bapak dan Ibu Anggota Senat, dosen se-Universitas Bung Hatta
Istimewa para undangan yang saya hormati
Hadirin yang saya hormati.
I. Pendahuluan.
Masyarakat negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, umumnya menghadapi masalah loyalitas, dari loyalitas yang kembar dan sempit kearah loyalitas nasional. Seandainya pembangunan loyalitas masyarakat ini diarahkan melalui mobilisasi, maka sebagai hasilnya seperti terlihat dalam periode Demokraksi Terpimpin, yaitu terjerumus ke arah sistem totaliter. Dengan demikian, jika kita mengharapkan pemerintahan yang demokratis, maka pembangunan loyalitas masyarakat harus diarahkan melalui partisipasi.
Untuk mendapatkan saluran yang tepat dan efektif bagi tumbuhnya partisipasi dalam masalah politik sangat tergantung pada bentuk demokrasi yang dikembangkan dan terjaga konsistensinya dalam praktek. Dalam konteks ini berdasarkan sistem politik yang pernah dianut di Indonesia, faktor pembeda antara demokrasi yang satu dengan yang lainnya terletak pada prosesnya. Dalam proses itu juga dipersoalkan bagaimana rakyat diajak turut serta dalam keputusan politik. Setiap keputusan politik yang diambil oleh suprastruktur politik, melaui proses konversi dikaitkan kembali dengan rakyat dan karenanya melibatkan rakyat.
Jika Pemilihan Umum (Pemilu) diklasifikasikan sebagai salah satu jenis partisipasi rakyat dalam politik, maka pertanyaannya adalah, apakah Pemilu 2004 akan membawa Indonesia keluar dari krisis partisipasi ketika banyak pengamat politik mempertanyakan jalur yang ditempuh Indonesia dalam konteks pembangunan politik.
Untuk menjawab pertanyaan di atas, orasi ilmiah ini akan mencoba melihat sejauh mana implikasi Pemilu 2004 bagi penguatan lembaga legislatif dan Pemerintahan yang aspiratif.
Hadirin yang saya hormati
II. Pemilu di Indonesia dan Hasilnya : Suatu Kilas Balik.
Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa saluran yang efektif dalam mengkoversi aspirasi rakyat tergantung pada bentuk demokrasi yang diyakini dan secara ril berlangsung. Ini tentu saja dengan memahami, bahwa salah satu manfaat yang diberikan demokrasi adalah memberikan kesempatan berupa kemerdekaan (freedom) bagi rakyat biasa untuk mengemukakan pendapat (aspirasi-pen) mereka. Namun perlu juga disadari bahwa bagaimana kesempatan itu diraih tergantung juga dari bagaimana kemerdekaan itu diungkapkan. Karenanya, demokrasi adalah wujud nyata bagaimana rakyat bisa menyalurkan aspirasi/partisipasinya kepada pemimpinnya. Prakteknya demokrasi itu di Indonesia tercermin dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.
Konsepsi demokrasi sebagai wujud partispasi politik rakyat itu di Indonesia sebelum tahun 2004 dipolakan dalam bentuk indirech democracy (demokrasi perwakilan). Pada taraf perwakilan inilah aspirasi/partisipasi politik rakyat bertarung dengan kepentingan dan kecenderungan keberpihakan elit politik yang mewakili rakyat. Sampai atau tidaknya, diperjuangkan atau tidak aspirasi ditingkat pengambilan keputusan sangat tergantung pada sikap dan kecenderungan politik sang wakil. Pada saat itu tengah diuji kadar kepemimpinan demokratis wakil rakyat. Dengan demikian, Pemilu sebagai media pengungkapan kemerdekaan dan sebagai saluran partisipasi rakyat akan sangat ditentukan oleh sistem Pemilu yang dipakai dan bagaimana prosesnya.
Sepanjang sejarah politik Indonesia, penyelenggaraan Pemilu dalam pandangan sebagian pengamat dan ahli politik masih berlangsung dalam ruang politik mobilisasi dan yang tampak adalah kirisis partisipasi. Sekali pun Pemilu tahun 1955 dinilai Jeffrey A. Winters , rakyat Indonesia merasakan Pemilu yang adil untuk pertama kali dan terakhir kalinya. Tetapi penilaian tersebut sekaligus menjadi petunjuk kian menurunnya kualitas Pemilu di Indonesia sebagai sarana bagi partisipasi rakyat dalam politik. Kondisi ini terjadi disebabkan banyak faktor dan yang utama adalah bentuk demokrasi yang dikembangkan di Indonesia.
Meski Pemilu tahun 1955 dinilai sebagai pemilu yang adil dan Pemilu tahun 1999 dinilai sebagai pemilu yang demokratis, namun keluaran dari kedua Pemilu tersebut tidak membawa kehidupan ketatanegaraan yang lebih baik sesuai dengan harapan rakyat. Ini setidaknya ditunjukkan oleh situasi Indonesia--sampai penyelenggaraan Pemilu 2004-pen) -- masih berada dalam political gray zone (zona politik abu-abu) . Dalam konteks political gray zone, seorang peneliti dari Carnegie Endowment for International Peace, Thomas Carothers, sebagaimana dikutip Bara Hasibuan, bahwa negara dalam zona abu-abu ini menganut sindrom feckless pluralism yang berarti, bahwa walaupun di permukaan negara-negara ini kelihatan demokratis, namun di dalamnya kualitas kehidupan politiknya ternyata bobrok.
Para elite politik termasuk juga parpol dinilai korup dan hanya mendahulukan kepentingan sendiri dan tidak peduli dengan nasib rakyat dan negara. Publik, walaupun masih percaya terhadap demokrasi, namun kecewa dan tidak percaya terhadap elite politik, partai politik (parpol), serta institusi publik lainnya. Politik dilihat sebagai sesuatu yang kotor, busuk dan didominasi segelintir orang yang tidak peduli dengan nasib bangsa. Pemerintahan baru yang demokratis pun dinilai tidak mampu untuk menangani berbagai masalah seperti korupsi dan kejahatan. Kenyataan ini tentu berlawanan dengan kosepsi perwakilan yang sesungguhnya, dimana perwakilan adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Tetapi realitasnya, perwakilan politik di Indonesia dipandang tidak memuaskan rakyat, bahkan eksistensinya digugat dari waktu-kewaktu.
Digugatnya peran lembaga legislatif (DPR-DPRD) sudah diperkirakan banyak pengamat selang belasan tahun yang lalu, bahkan tidak terkecuali terhadap DPR-DPRD hasil Pemilu 1999. Hal ini setidaknya tampak dari datangnya berbagai kelompok masyarakat yang mencari penyelesaian masalah mereka ke badan legislatif. Bahkan setelah era reformasi pun peran DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat masih menjadi issu sentral. Rakyat datang ke DPR tidak lagi sekedar menuntut peran DPR menyelesaikan masalah-masalah mereka, tetapi justru menggugat eksistensi dan tindakan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Mengapa hal itu bisa terjadi ? Bukankah Pemilu tahun 1999 telah berlangsung secara demokratis!
[newpage]
Jawaban dari pertanyaan di atas setidaknya tergambar dari apa yang pernah dikemukakan A.Mustofa Bisri, bahwa kita akan bisa melihat bagaimana di zaman reformasi ini, ajaran rezim Soeharto masih utuh dipraktikkan dan diamalkan oleh tokoh-tokoh dari berbagai kalangan. Bisakah anda membedakan tokoh-tokoh itu dengan dengan tokoh-tokoh rezim Soeharto ? Dikemukakan pula, bahwa banyak orang, termasuk sementara pemimpin dan reformis, yang sudah sangat fasih ââ¬âmenirukan ââ¬Åguruââ¬Â mereka kemaren-- menonjolkan kepentingan sendiri atau kelompok; sangat terampil memaksakan kehendak; sangat lihai merekayasa; sangat cekatan menyalahkan orang lain; sangat canggih mempermainkan hukum; sangat tega mengorbankan anak sebangsa; sangat mahir mengatas -namakan rakyat; sangat pintar menggunakan ayat untuk kepentingan; bahkan sangat berani menyaingi Tuhan dengan berlagak arogan dan mutlak-mutlakan.
Karena itu, Pemilu 1999 yang tadinya dinilai sebagai pemilu yang demokratis, tetapi out-putnya justeru mempertebal political gray zone dan belum mampu mendorong lahirnya pemerintahan Indonesia yang aspiratif dalam kerangka walfare state. Hal ini menubuhkan keyakinan yang kuat pada kita, betapa pentingnya untuk setiap keputusan politik yang diambil suprastruktur politik melalui proses konversi dikaitkan kembali dengan rakyat dan karenanya melibatkan rakyat. Pemilu 1999 justeru persoalannya terletak di sana, dimana volume harapan dan tuntutan rakyat tidak mendapat wadah yang cukup dalam suprastruktur politik.
Dipenghujung tahun 2001 Presiden Megawati Soekarno Putri pernah menyatakan, bahwa kenyataan objektif menunjukkan bahwa pihak legislatif mengalami eforia. Terlepas bagaimana respon kalangan legilastif atas kritik yang dilontarkan Preseden itu, kecenderungan legislatif mengalami eforia sukar dipungkiri. Meskipun hal itu sesuatu yang alamiah, tetapi eforia yang berbasiskan pada ââ¬Åpertarunganââ¬Â politik dan berorientasi kekuasan tidak cocok dengan mission yang diemban badan legislatif. Apa yang dilakukan badan legislative masih jauh dari harapan masyarakat secara umum. Semestinya begitu menjadi anggota DPR tidak peduli dari partai mana pun, mereka menempatkan diri sebagai wakil rakyat. Namun kenyataannya, DPR kadang kala mengartikulasikan isu yang jauh dari kepentingan publik.
Kini ââ¬âsetidaknya sampai tahun 2004-- keadaannya belum banyak berubah. Komitmen politik lembaga legislatif yang responsif terhadap isu yang menyentuh kepentingan publik masih jauh dari yang diharapkan. Perekonomian negara yang terpuruk menembus pintu pertahanan krisis tidak lebih ââ¬Ånyaringââ¬Â dan ââ¬Åintensââ¬Â diperdebatkan legislatif. Bahkan dibeberapa daerah sejumlah anggota DPRD justeru harus berhadapan dengan Pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Kalau begitu, harapan apa yang dapat ditumpangkan rakyat kepada anggota legislatif sebagai wakil mereka untuk melepaskan diri dari himpitan kesulitan ekonomi ? Nantilah dulu soal bagaimana menjadikan rakyat makmur.
Di sisi lain pembaharuan undang-undang telah menempatkan DPR-DPRD pada posisi legislative heavy yang sangat mencolok dan sangat berbeda dari legislatif Zaman Orde Baru. Sayangnya, kedudukan dan fungsi legislatif yang kuat itu tidak dimamfaatkan untuk kepentingan publik dalam arti yang sesungguhnya. Sering-sering hal-hal yang kasuistis diberi label sebagai kepentingan publik. Fungsi politik (kontrol) DPR terkadang berujud ââ¬Åmenyerangââ¬Â eksekutif, dan tidak jarang berakhir dengan ââ¬Åpertikaian internalââ¬Â dilembaga legislatif sendiri.
Padahal fungsi kontrol (politik) bukanlah segala-galanya bagi legislatif, meskipun penting dari sisi demokrasi. Tetapi, trend pemanfaatan fungsi politik ini sangat mendominasi lembaga legislatif dan di daerah bahkan eksekutif sering dibikin ââ¬Åpanikââ¬Â oleh legislatif. Bila tidak ââ¬Åpandai-pandaiââ¬Â menjaga hubungan baik dengan legislatif, seorang Gubernur/Walikota/Bupati bakal menghadapi ââ¬Åkesulitanââ¬Â. Dalam konteks ini, menjadi relevan, bahwa lembaga ini mengalami eforia (eforia politik). DPR cenderung belum menomor-satukan tugas legislasinya, sekalipun itu merupakan tugas pokok dan wahana utama untuk merefleksikan kepentingan rakyat (publik). Sebagaimana dikemukkan Rusadi Kantaprawira, bahwa arah dari kehidupan bersama di masa mendatang pada hakikatnya sudah ditentukan lebih dahulu (predetermined). Rambu-rambu pembatasan dari segala usaha kenegaraan itu secara awal sudah ditetapkan dalam wujud legislasi yang berisi regulasi yang terpokok, yang cakupannya jauh ke depan dan diharapkan dapat berumur panjang, tidak cepat lapuk.
Dalam perubahan yang tengah berlangsung di Indonesia, seharusnya badan legislative hasil Pemilu 1999 telah ââ¬Åmemainkanââ¬Â fungsi dan tugasnya secara efektif dan berdayaguna; melepaskan diri dari budaya politik kepentingan atau kelompok; dan tidak digugat oleh rakyat yang diwakilinya. Namun, masalah itu yang menjadi hambatan baru bagi perujudan dan optimalisasi peran legislasi DPR. Tidak mudah memang untuk mecapai peran serupa itu, karena peran legislasi DPR akan terwujud apabila visi mewakili rakyat sudah melembaga dengan baik, sesuai harapan rakyat. Dalam perspektif ini dapat pahami, betapa Pemilu tidak boleh sekedar atau sebatas dirasakan adil atau demokratis semata, melainkan bagaimana Pemilu menjadi jembatan bagi terwujudnya perubahan orientasi politik kekuatan menjadi orientasi politik berdasarkan program yang tidak sebatas janji kampanye atau retorika untuk ââ¬Åmenarikââ¬Â massa.
Perubahan orientasi itu hanya dapat terjadi apabila konfigurasi masyarakat secara menyeluruh ââ¬Ådiubahââ¬Â terlebih dahulu. Konfigurasi masyarakat yang didasarkan pada pola ââ¬Ånunut kepada panutanââ¬Â atau didasarkan kepada kepartaian menurut pola aliran misalnya, perlu ditata terlebih dahulu. Sementara itu pada saat penyelenggaraan Pemilu tahun 1999 situasinya konfigurasi masyarakat dalam ketidak puasan pada sistem kepartaian pada masa Orde Baru dan melahirkan sistem multiââ¬âpartai sebagai implikasi dari pandangan demokrasi di Indonesia sudah lama ââ¬Åsekaratââ¬Â.
Sistem multi-partai yang mengiringi Pemilu 1999 sebagai bagian dari tuntutan reformasi tidak diperhitungkan secara cermat sebagai sarana memodernisasikan masyarakat, dan melupakan bahwa sistem multi partai relatif lebih mudah menumbuhkan instabilitas dari pada di negara yang menganut sistem satu-partai, atau sistem satu setengah partai atau pun sistem dua-partai. Pada hakikatnya sistem multi partai itu tidak banyak berbeda dengan tiadanya partai dalam masyarakat. Dengan demikian, jika timbul kekecewaan terhadap badan legislative dan pemerintah hasil Pemilu 1999 semestinya sudah bukan hal yang mengherankan dan kita tidak perlu heran, mengapa situasi Indonesia sampai saat ini masih berada dalam political gray zone. Artinya, bangsa ini dengan tergesa-gesa mengambil keputusan menerapkan sistem multi-partai yang tidak terkontrol, yang susungguhnya berlawanan dengan kondisi ââ¬Åkrisis beratââ¬Â yang melanda Indonesia membutuhkan stabilitas. Bahkan dari sisi keadaan pemerintahan stabil pun, sistem multi partai yang kita kembangkan tidak cocok pula dengan apa yang berlansung dinegara maju dan stabil pemerintahannya seperti Amerika Serikat yang tidak menganut sistem multi partai.
Kondisi tersebut memang tidak hanya terjadi di Indonesia. Fenomena ini merupakan ciri yang lazim dinegara berkembang, meskipun kadarnya berbeda dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang lain. Lagi pula gambaran keadaan yang berlansung sekarang itu, sebetulnya bukan situasi baru. Herbert Feit tahun 1964 dalam bukunya "The Declines of Constitutional Democracy in Indonesia", menganalisis; bahwa demokrasi dilihat sebagai tujuan yang harus dicapai dimasa yang akan datang. Hal itu sesuai dengan orientasi masa depan yang merupakan pandangan hidup yang penting dalam pimpinan nasional Indonesia, yaitu kecenderungan untuk hanya memikirkan keadaan masa depan dari pada memikirkan pembaharuan pragmatis terhadap kenyataan yang ada. Dalam hemat kita, apa yang dikemukakan Herbert Feit telah begitu lama diabaikan elit politik di Indonesia, tidak terkecuali setelah era reformasi bergulir di Indonesia.
[newpage]
Hadirin yang berbahagia
III. Sistem Kepartaian di Indonesia: Kritik Terhadap Sistem Multi Partai.
Jika belasan tahun yang lalu para ahli politik Indonesia mempertanyakan, sistem kepartaian yang bagaimanakah yang cocok dikembangkan di Indonesia? Pertanyaan ini masih relevan sampai saat ini karena sistem multi partai yang dikembangkan sejak pasca Orde Baru belum menemukan bentuknya yang sesuai harapan rakyat. Apakah sistem ââ¬âmulti partai sudah merupakan pilihan yang tepat ditumbuhkan kembali di Indonesia ketika yang diperlukan rakyat perbaikan perekonomiannya?
Pemilu 1955 misalnya yang dikuti lebih kurang 40 organisasi peserta, yang menurut Jeffri A.Winters, rakyat Indonesia merasakan pemilu yang adil untuk pertama dan terakhir kalinya, tetapi ada yang dilupakan Winters, bahwa setelah Pemilu tahun 1955 partai-partai politik merasa mempunyai legalitas dan memperoleh kekuasaan politik secara formal. Sejak saat itu, dalam politik Indonesia, partailah yang memegang kekuasaan politik; walaupun dalam kenyataannya kepemimpinan politiknya dilakukan atas kerja sama, aliansi, koalisi antara dua kekuatan atau lebih. Dalam hubungan ini Rusadi Kantaprawira mengemukakan, bahwa kelemahan kepemimpinan partai politik ini kemudian terbukti, yaitu, tidak dapat menyelesaikan, misalnya, segala masalah yang dihadapi oleh antara lain Konstituante dalam menetapkan UUD yang baru.
Atas kegagalan kepemimpinan partai-partai menghadapi tantangan sistem politik Indonesia, dan sebagai konsekuensi pelaksanaan berlakunya kembali UUD 1945 Presiden mengeluarkan serangkaian peraturan yang salah satunya adalah Penetapan Presiden (Penpres) mengenai syarat-syarat dan penyederhanaan Kepartaian. Penpres tersebut hanya menghasilkan 10 partai yang mempunyai hak hidup, sedang selebihnya tidak dapat diakui karena tidak memenuhi syarat. Hal ini dikemukakan terlepas dari dimensi politik yang berlangsung pada saat itu, karena yang terpenting adalah, bahwa kita pernah mempunyai pengalaman dengan sistem-multi partai yang ternnyata tidak efektif dalam mewujudkan kehidupan kenegaraan yang stabil dan memberi stimulan bagi tumbuhnya politik partisipasi.
Pada pada pasca Orde Baru, sistem multi partai yang pernah dipraktekan dalam kehidupan politik di Indonesia kembali dihidupkan meskipun pada waktu dan situasi politik yang berbeda. Kehidupan kepartaian pada pasca Orde Baru setidaknya ditandai dengan lahirnya 150 partai politik baru dan 48 diantaranya masuk seleksi untuk ikut Pemilu tahun 1999. Namun sistem multi partai yang dikembangkan pasca Orde Baru kelihatannya lebih dominan sebagai pelampiasan atas pengekangan jumlah partai yang hanya disederhanakan menjadi 3 partai saja yang berlangsung selama belasan tahun. Pada lain kesempatan dilihat sebagai kian otoriternya pemerintahan Orde Baru. Dalam konteks ini jelas implikasi sistem multi partai yang berlangsung pada tahun 1955 tentu tidak sama dengan implikasi sistem multi partai pada pasca kejatuhan Orde Baru. Tetapi, satu hal yang mirip ââ¬â meskipun tidak sama-- yakni situasi yang mewarnai badan legislative dan kepemimpinan nasional Indonesia pada pasca Pemilu 1955 juga berlangsung pada badan legislative dan kepemimpinan nasional Indonesia pasca Pemilu 1999. Dalam hal ini tidak adanya mayoritas mutlak dalam lembaga perwakilan rakyat, melahirkan koalisasi, kerjasama dua atau lebih kekuatan politik atau pun melahirkan politik kompromi. Kejatuhan Presiden Abdul Rahman Wahid adalah satu akibat dari sistem multi partai tersebut.
Dari beberapa catatan mengenai sistem multi partai dapat dimengerti, bahwa sistem multi partai tanpa batas tidak sepenuhnya cocok dengan pembangunan politik Indonesia dan sangat sulit bagi tumbuhnya partispasi rakyat dalam politik. Kecenderungan justeru, Indonesia akan berlama-lama hidup dalam kehidupan politik mobilisasi. Keadaan itu pada gilirannya eksistensi lembaga perwakilan rakyat tetap menjauh dari konsepsi perwakilan yang sesungguhnya. Keadaan ini pada waktu-waktu mendatang akan dirasakan Indonesia, karena sampai pada penyelenggaraan Pemilu 2004 sistem multi partai tanpa batas masih berlangsung dan menjadi beban baru rakyat apabila tidak ada keberanian politik di Indonesia mengambil kebijakan sistem multi-partai terbatas. Dan disisi lain menekan tumbuhnya kecenderungan pembentukan partai politik ââ¬Åpatah tumbuh, hilang bergantiââ¬Â. Permasalahan ini menjadi sangat subtasial, apabila partai politik menjadi satu-satunya pemasok bagi pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di Pusat maupun Daerah.
[newpage]
Hadirin yang saya hormati
III. Pemilu 2004 dan DPR Kita : Harapan dan Tantangan.
Belajar dari apa yang terjadi dalam dunia politik Indonesia setelah tahun 1999, memperlihatkan konfigurasi partai-partai politik yang membingungkan, karena begitu mudah dan cepatnya terjadi perubahan. Nyaris tak bersisa adanya perspektif politik yang bisa dijadikan pegangan untuk menilai arah kepolitikan masa datang. Politik telah jatuh pada titik paling ekstrem, yaitu bagian dari konsep Thomas Hobbes sebagai pengejawantahan homo homini lupus, sekalipun belum sampai pada konsepsi Louis ke-XIV, le 'etat est moi. Hal ini setidaknya ditunjukkan oleh sejumlah peristiwa yang terjadi di DPR yang lebih dominan mempersoalkan kekuasaan dengan segala implikasinya ketimbang memikirkan nasib rakyat.
Citra DPR yang terbentuk Pasca Pemilu 1999 boleh jadi bagi sebagian orang akan dimaklumi sebagai sebuah kewajaran dalam masa transisi, namun kita lupa betapa mahal biaya yang kita keluarkan untuk sebuah hasil yang menimalââ¬âapalagi negara tengah mengalami krisis ekonomi ââ¬Åakutââ¬Â. Pada konteks inilah kita sampai pada pemahaman akan pentingnya komitmen politik para politisi yang bakal ââ¬Åmebidaniââ¬Â DPR melalui Pemilu Tahun 2004 ini. Dan jauh lebih penting adalah legislative daerah harus tidak saja menunjukkan keinginan untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih luas, tetapi juga kesiapan untuk mengimplementasikannya. Sehingga untuk menempatkan peran dan eksistensi DPR pada posisinya yang sesungguhnya menuntut adanya perubahan prilaku elite lokal yang duduk di DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal yang kita sebut terakhir ini ââ¬âperubahan prilaku elite lokalââ¬â menjadi sama pentingnya dengan upaya mendorong kelembagaan DPR menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya. Jika secara teoritis dan yuridis formal DPR menjalankan fungsi-fungsi yang tradisional legislatif, tetapi secara moralitas anggota DPR mempunyai kewenangan tidak sekedar menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Dalam konsepsi yang lebih luas, eksistensi DPR merupakan penentu arah kebijaksanaan politik di Indonesia. Namun realitasnya, DPR kita belum sepenuhnya berpihak dan menyuarakan kepentingan rakyat. Kenyataan ini mengundang pertanyaan, anggota DPR sebenarnya mewakili siapa ? Pertanyaan ini tentu menyentuh sisi moralitas anggota legislatif dalam pertanggung jawaban atas kepercayaan yang diberikan rakyat.
Bahwa, moralitas adalah prinsip yang harus dijalankan tanpa tawar-menawar agar seseorang dapat menjadi manusia, dan bukan kadal berkaki dua. Sebaliknya, secara fungsional, moralitas amat dibutuhkan, karena tanpa beberapa pedoman mengenai baik dan buruk, kehidupan bersama tak dapat diatur. Dari sisi ini, moralitas adalah suatu fungsi yang amat penting. Tanpa ada peraturan mengenai penghormatan kepada hak hidup dan hak milik orang lain, kehidupan dalam sebuah desa yang terpencil atau pekerjaan dalam sebuah kantor kecil menjadi centang-perenang dan tak dapat diatur.
Masalahnya kemudian, bagaimana kita menghadapi masalah baik dan buruk ini dalam lembaga legislatif Indonesia ? Apakah hasil Pemilu tahun 2004 akan memberikan jawaban atas pertanyaan ini ? Hal ini masih merupakan sesuatu yang sukar untuk diberikan jawaban positif, karena sampai saat ini dunia politik Indonesia masih berlangsung dalam politik mobilisasi dan sistem pemilu yang dipergunakan belum mampu memenuhi kebutuhan penciptaan sumber daya manusia bagi pemenuhan terwujudnya lembaga legislatif sesuai dengan konsepsi perwakilan yang hakiki. Meskipun terlihat adanya modernisasi politik, namun belum sepenuhnya berkembang dalam paradigma modernisasi, dimana sistem politik yang modern dikarakterisasikan dengan mobilisasi sosial dan partisipasi. Di sisi lain mobilisasi dan partisipasi politik harus sejalan dengan pengorganisasian dan institusionalisasi guna menghindari terjadinya skenario-skenario kekacauan yang kontraproduktif bagi proses demokratisasi. Keadaan demikian, memberikan gambaran akan kualitas penerapan konsep perwakilan di Indonesia.
Apabila perwakilan adalah suatu konsep yang menunjukkan hubungan antara dua orang atau lebih, yakni antara wakil dengan pihak yang diwakili (terwakili), dimana wakil mempunyai sejumlah wewenang yang diperoleh melalui kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya. Atas dasar ini, maka badan legislative harus dapat berfungsi sebagai cermin dari kualitas tatanan masyarakat yang ada. Dalam persepktif ini lembaga legislatif hasil pemilu tahun 1999 tidak sepenuhnya pencerminan dari kualitas person wakil rakyat secara individu karena ada indikasi "pengingkaran" terhadap konsepsi perwakilan dan tidak ada jaminan untuk ditaati. Meskipun Gebriela Almon telah mengingatkan, bahwa di dalam masyarakat demokratis out put peraturan, ekstraksi dan distribusi lebih dipengaruhi oleh input dari permintaan dari kelompok dan karenanya masyarat memiliki kemampuan responsif yang lebih tinggi (Ronald H. Chillcote;1981). Tetapi itulah masalahnya, anggota legislatif kita sepertinya "berjarak" dengan rakyat yang diwakilinya dan kecenderungannya berperan sebagai seorang birokrat.
Menghadapi perkembangan yang tidak menguntungkan bagi tumbuhnya demokrasi rakyat, terlebih dengan semakin tingginya tingkat responsif dan kesadaran akan hak-hak politik mereka, sistem pengisian anggota legislatif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2003 yang menganut sistem proposional terbuka, ternyata belum memadai dan tidak sepenuhnya dapat menuntaskan berbagai kritik dan sorotan terhadap DPR hasil Pemilu 1999. Namun demikian, sebuah kesepakatan politik nasional untuk menerapkan Pemilu untuk pemilihan anggota legislative dan presiden secara langsung merupakan alternatif perubahan politik yang rasional yang seharusnya sudah dikembangkan di Indonesia ketika peran dan eksistensi DPR/MPR tidak lagi aspiratif dan demokratis.
Bahwa di negara-negara demokratis pemilu dianggap sebagai lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan, seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi para warga negara. Hal ini memberikan pembenaran kepada kita, bahwa masa depan dan esksistensi DPR-DPRD akan sangat tergantung pada sistem dan proses pemilihan umumnya.
[newpage]
Terhadap masalah yang dikemukakan di atas, pertanyaannya adalah pemilu dengan sistem yang mana yang kontributif bagi perujudan keinginan pengisian anggota dewan yang demokratis dan aspiratif di Indoensia ? Kita mengenal dua sistem pemilu yang masing-masing dengan beberapa variasinya. Pertama pemilu dengan sistem proporsional; kedua, pemilu dengan sistem distrik. Sistem distrik sering dipakai dalam negara yang mempunyai sistem dua-partai, seperti Inggris dan Amerika. Sedangkan sistem proporsional sering diselenggarakan dalam negara banyak partai, seperti Swedia, Itali dan Indonesia.
Sistem distrik dengan sistem menghitung perolehan suaranya akan terjadi banyak suara wasted, dan karenanya sistem distrik dianggap tidak repsentatif karena tidak memperdulikan suara mereka. Tetapi sistem distrik potensial untuk mencegah timbulnya partai baru, karena bagi partai baru sukar untuk memenangkan suatu distrik. Konsekuensinya, dengan sistem distrik dapat menghasilkan penyederhanaan partai secara alamiah dan fragmentasi partai dapat dicegah. Di lain pihak dengan sistem distrik kesenjangan jumlah suara yang diperoleh satu partai dan jumlah kursi yang diperolehnya, selalu menguntungkan partai besar dan merugikan partai kecil.
Tetapi harus diakui, bahwa dengan sistem distrik bisa dicegah mayoritas dalam lembaga legislatif. Karena pada sistem distrik hanya diperlukan pluralitas suara dan wakil-wakil yang dipilih melalui sistem distrik erat hubungannya dengan rakyat yang diwakilinya. Anggota Legislatif yang dipilih lebih berorientasi pada kepentingan distrik, serta kepentingan warga masing-masing. Walau pun begitu, tidak berarti anggota dewan itu betul-betul independen, dan tidak berarti sama sekali bebas dari pengaruh partainya, dimana dukungan serta fasilitas partai diperlukannya baik untuk nominasi maupun untuk kampanye.
Berbeda dengan sistem distrik, pemilu dengan sistem proporsional dipandang lebih demokratis dan representatif, dalam arti bahwa jumlah wakil partai sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilu secara nasional, dan semua golongan sekecil apapun mempunyai peluang untuk menampilkan wakilnya dalam badan legislative dan tidak ada distorsi seperti pada sistem distrik. Masalahnya mungkin terletak pada kuatnya kedudukan partai melalui sistem daftar dan anggota legislative yang terpilih cenderung kurang erat hubungannya dengan warga yang memilihnya, dan peranan partai lebih menonjol. Sebab partai yang memasukkan namanya dalam daftar calon, maka si wakil akan lebih memperhatikan kepentingan partai serta masalah-masalah umum dan nasional, ketimbang memperhatikan kepentingan masyarakat dan daerah pemilihannya.
Memahami kelemahan dan kelebihan kedua sistem pemilu tersebut, sistem proporsional bisa dikatakan lebih demokratis, tetapi belum tentu aspiratif. Sedangkan sistem distrik memang lebih aspiratif, tetapi belum tentu demokratis. Sebagai upaya pengisian anggota legislatife ââ¬âtermasuk legislative daerahââ¬âdengan sistem pemilu yang dianut UU Nomor 12 Tahun 2003 meskipun demokratis, tetapi belum aspiratif. Ada kemungkinan konsepsi perwakilan akan mengalami shock yang luar biasa karena sistem prosporsional terbuka yang dianut undang-undang pemilu yang baru itu ââ¬Ådikunciââ¬Â dengan sistem nomor urut sebagaimana pada sistem proporsional tertutup.
Pola sistem pemilu yang dianut UU Nomor 12 Tahun 2003 bukan sekedar kealfaan, melainkan menggambarkan situasi politik yang berlangsung di DPR kita. Keputusan politik itu sangat merugikan pembangunan politik rakyat dan akan mempengaruhi eksistensi badan legislative sebagai organ demokrasi. Artinya, eksistensi dan peran DPR sebagai lembaga perwakilan dalam artian yang sesungguhnya dengan sistem Pemilu dibawah UU Nomor 12 Tahun 2003 sangat tergantung pada ââ¬Åkecerdesanââ¬Â pemilih dalam memilih calon legislatif yang akan mewakilnya.
Masalahnya justeru ada pada soal kecerdesan pemilih itu, seberapa banyak calon legislatif daerah yang ditawarkan partai perserta pemilu 2004 yang dikenal pemilih. Kalau toh ada satu atau beberapa calon yang dikenal masyarakat, tapi duduk pada nomor urut bawah. Sang calon tidak bakal dapat duduk di DPR mewakili masyarakat ketika jumlah suara yang diraihnya tidak memenuhi BPP, meskipun hanya kurang satu suara. Suara yang diraih sang calon tadi justeru beralih ke nomor urut 1 yang sebenarnya tidak mendapat dukungan suara, katakanlah hanya 0,1 persen dari BPP yang sah. Padahal pada Pemilu Tahun 2004 partai politik merupakan satu-satunya pemasok anggota legislative pusat maupun daerah.
Dengan demikian sukar dibantah, meskipun sistem kepartaian di Indonesia telah memberi peluang untuk membentuk partai-partai baru, namun eksistensi badan legislatif sesuai harapan rakyat masih mendapat ganjalan yang masalahnya utama terletak pada sistem pemilu yang dipergunakan. Dalam konteks ini secara tidak langsung optimalisasi fungsi-fungsi pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah menjadi semakin kompleks. Apa yang kita hadapi sekarang tidak juga tidak terlepas dari beberapa tipe demokrasi yang dikembangkan di Indonesia yang gagal mewujudkan suatu bentuk pemerintahan yang berfungsi.
Bila pada masa sebelum lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 sedikitnya ada dua alasan utama mengapa pendulum desentralisasi dan otonomi daerah pada masa Orde Baru cenderung mengayun ke arah kutub sentralisasi; Secara politis, fenomena ini terjadi karena adanya keinginan yang kuat dari pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas politik dan ketahanan nasional. Sedangkan alasan ekonominya, kecenderungan sentralisasi kekuasaan tersebut berkaitan dengan kehadiran model Neo-Keynisian yang telah digunakan oleh para teknorat dalam merancang model pembangunan ekonomi Orde Baru. Model ini, tegas Kuntjara Jakti, tidak dapat dipungkiri memang lebih menghendaki adanya sentralisasi kekuasaan.
Pasca reformasi tahun 1998 diantara restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting adalah adanya upaya untuk mengoreksi sistem pemerintahan yang sentralistik ke sistem pemerintahan yang desentralistik dengan memperluas otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan DPRD tidak lagi sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Konsepsi undang-undang pemerintah daerah yang baru itu luput dari perhatian UU Pemilu Nomor 12 Tahun 2003, bahwa yang berotonomi itu sebenarnya adalah rakyat daerah. Namun sistem Pemilu berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003 dapat dikatakan masih dominan mempertimbangkan kepentingan partai, ketimbang kepentingan rakyat. Sistem pemilu kita masih menempatkan rakyat sebagai objek Pemilu dan tidak sebagai subjek yang sesungguhnya pemilik Pemilu itu sendiri. Ini setidaknya ditunjukkannya prilaku politik anggota legislatif yang tidak lagi mendekati konstituennya ketika Pemilu usai. Dan menjadi suatu pemandangan yang aneh ketika seorang calon legislatif, berbaik-baik, berjoget bersama dan mendatangi rakyat Pemilu ketika kampanye Partai, bahkan mau datang jauh-jauh dari Ibukota Negara dari kota-kota kepelosok-pelosok, tetapi mereka menjadi sulit ââ¬Ådisapaââ¬Â ketika sudah menjadi anggota badan legislatif.
Jika hal itu yang terjadi nanti, apa maknanya ââ¬ÅPemilu 2004 Bedaââ¬Â selain dari sekedar rakyat bisa milih lansungââ¬Â. Hal ini mengingatkan kita kembali pada pertanyaan, betulkah Indonesia saat ini ada pada jalur yang benar dalam konteks pembangunan politik ? Sebagaimana dikemukakan Bima Arya Sugiatro, bahwa mobilisasi dan partisipasi politik yang tinggi dan tidak disertai dengan pengorganisasian dan institusionalisasi bukanlah merupakan prakondisi yang tepat bagi terciptanya masyarakat madani, melainkan kondusif bagi skenario-skenario kekacauan yang kontraproduktif bagi proses demokratisasi. Hal ini dapat dicermati dengan mudah pada waktu-waktu mendatang.
Kekacauan yang kontraproduktif bagi proses demokratisasi dalam pengertian akademis dapat diterjemahkan tidak kita punyai organ demokrasi seperti DPR yang menjauh dari kepentingan rakyatnya sendiri. Indikasi itulah yang antaranya masih disisakan UU Nomor 12 Tahun 2003 pada saat rakyat mengantunkan harapan kepada DPR untuk dapat berfungsi dengan efektif , ketimbang sekedar membolak-balik tugas dan fungsinya yang dimuat dalam undang-undang.
[newpage]
Hadirin yang saya hormati
IV. Mengubah Sistem Pemilu Pasca Pemilihan Umum 2004.
Situasi sistem kepartaian di Indonesia yang digandengkan dengan sistem Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 memang menunjukan wajahnya yang berbeda dengan sistem Pemilu yang dipakai pada Pemilu tahun 1999. Namun, dengan sistem multi partai dan system Pemilu 2004 sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 ternyata tidak membebaskan Indonesia ini dari ââ¬Åkekisruhanââ¬Â kehidupan politik.
Jika pada rezim Orde Baru penekanan pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi sebagai landasan utama legitimasi. Efeknya, partai politik yang dianggap akan menjadi sumber ketidak stabilan perlu di kelola sehingga berhenti sebagai sumber instabilitas (Ichlasul Amal dan Reza Pangabean; 1993;293) . Pada saat ini, tampaknya keberadaan partai politik pun masih menjadi sumber ketidakstabilan. Dan jika pada rezim Orde Baru mencoba memupuk satu partai politik untuk menggolkan kebijaksanaannya melalui anggota legislatif dari partai bersangkutan, pada saat sekarang justeru koalisi dan konsensus politik antar partai yang tidak konsisten yang mengoyang stabilitas politik. Kondisi serupa tampaknya masih akan berlansung Pasca pemilihan calon anggota legislatif Pemilu 2004, walau pun dalam rupanya yang lain. Hal ini dapat diamati dengan mudah undang-undang menentukan bahwa yang berhak mencalonkan Presiden adalah partai-partai yang memenuhi persentase tertentu dalam pemilihan legislative. Artinya, kehidupan politik yang dianut di Indonesia belum memiliki keberanian untuk melepaskan diri dari memutus hubungan paralel antara badan legislatif dengan badan eksekutif dan dibelakangnya bediri partai politik. Sehingga Pemilu legislative maupun Pemilu Presiden tetap saja berorientasi pada kekuasaan yang dibangun diatas kualiasi-kualisi partai.
Dalam konteks ini, peranan pemerintah yang berkuasa tampaknya masih akan menentukan kinerja dan keputusan politik yang diambil DPR. Hal ini terutama karena Presiden dan Wakil Presiden dan menteri masih memiliki ikatan formal dengan partai. Jika pada rezim Orde Baru eksekutif duduk sebagai Dewan Pembina partai politik tertentu, pasca rezim Orde Baru bukan hanya menjadi Pembina, melainkan pucuk pimpinan dari Partai politik itu sendiri. Bahkan siapa pun yang menjadi Presiden, tidak mudah baginya untuk memilih apakah akan mendahulukan kepentingan rakyat atau akan mendahulukan kepentingan partai, dan kebijakan eksekutif yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, akan mendapat pembelaan dari badan legislative terutama yang mencalonkan Presiden/Wakil Presiden.
Dengan demikian, meskipun anggota legislatif dipilih lansung oleh rakyat dan Presiden/Wakil Presiden juga dipilih lansung oleh rakyat, tetapi tataran pelaksanaan pemerintahan keduanya akan bertemu pada satu titik yang ââ¬Åmengempaskanââ¬Â suara rakyat. Dalam konteks ini, berdasarkan hasil Pemilu legislatif 2004 meskipun pemilu legislatif berbeda dengan pemilu Presiden, tetapi jalannya pemerintahan agaknya tidak akan jauh berbeda dengan keadaan sebelum tahun 2004. Dengan kata lain, Pemilu 2004 hanya berbeda dalam sistem dan cara, tetapi belum memberikan perbedaan pada penyelenggaraan pemerintahan secara subtantif. Dalam hubungan ini sistem dianut UU Nomor 12 Tahun 2003 dan melihat berbagai persoalan yang terjadi disekitar Pemilu 2004. maka UU Nomor 12 Tahun 2003 harus direvisi, antara lain mengenai;
Pertama, merubah sistem proporsional terbuka yang digandeng dengan sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka murni.
Kedua, merubah sistem pelimpahan suara dalam menentukan calon terpilih dari calon yang banyak memperoleh suara tetapi tidak mencukupi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dialihkan kepada calon yang memperoleh suara sedikit tetapi menempati nomor urut kecil, kepada sistem pelimpahan suara kepada yang memperoleh suara terbanyak tetapi tidak mencukupi BPP dicukupi oleh perolehan suara yang sedikit.
Ketiga, Merubah ketentuan yang menusuk nama saja ditempatkan sebagai suara tidak sah menjadi sama sahnya apabila hanya menusuk tanda gambar.
Keempat, menentukan kewajiban mensosialisikan dan menyebarkan secara luas kepada publik daftar nama calon legislatif, sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum Pemilu dilaksanakan.
Beberapa perubahan dikemukakan di atas tentu saja bila pada pemilu tahun 2009 masih mempertahankan sistem proporsional. Tidak demikian halnya apabila pemilu 2009 akan menggunakan sistem distrik, maka pemikiran perubahan kedua, ketiga sebagaimana dikemukakan di atas tetap menjadi suatu hal harus diutamakan. Apabila sistem distrik yang dipilih, maka UU Pemilu yang baru harus sudah selesai setidak-tidaknya dua tahun menjelang Pemilu 2009 dilaksanakan. Ini tentu saja bila kita mau belajar kelemahan pada sistem Pemilu 2004 dan ada keinginan yang sungguh-sungguh dari elit politik untuk membangun Negara Indonesia yang lebih baik, dan mengharapkan terwujudnya konsepsi perwakilan rakyat yang sebenarnya pada lembaga legislatif
Keperluan merubah sistem Pemilu itu, sekaligus perlu adanya pemikiran yang rasional dan tidak mesti diterjemahkan sebagai pelangaran konstitusi dan HAM, yakni kesepakatan nasional mengembangkan sistem multi-partai yang terbatas. Artinya tidak akan ada partai politik baru dua tahun menjelang Pemilu dilaksanakan., sehingga UU Partai Politik harus direvisi sejalan dengan revisi UU Pemilu.
[newpage]
Hadirin yang saya hormati
V. Penutup.
Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, implemtasi sistem perwakilan dibawah UU Nomor12 Tahun 2003 meskipun responsif terhadap perubahan dan dinamika social, namun belum mampu memberi space bagi bagi terangkatnya partisipasi aspirasi politik masyarakat dan mencerminkan kekuatan-kekuatan di masyarakat pemilih dan menubuhkan pemerintahan yang manpu mewujudkan walfere state yang tidak hanya di atas kertas.
Dalam konteks ini makna demokratis dan aspiratifnya pengisian anggota DPR pertama-tama harus dikonsepsikan sesuai dengan jiwa UUD 1945, bahwa kedaulatan ditangan rakyat. Meskipun pengisian anggota DPR yang demokratis dan aspiratif tidak hanya diperhitungkan dari segi bagaimana orang memilih wakilnya yang terkonsepi pada sosok individual. Namun untuk terciptanya suatu mekanisme perwakilan yang mampu secara memadai mencerminkan keanekaragaman kepentingan dan aspirasi di masyarakat, persoalannya justeru terletak disana.
Akhirnya perkenakanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Bung Hatta atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan tugas mulia ini dalam rangka Dies Natalis Universitas Bung Hatta ke 23. Kepada hadirin, Guru Besar, pejabat pemerintah dan para undangan, teman sejawat staf pengajar dan para mahasiswa saya ucapkan terima kasih atas kesabaran dalam mengingikuti orasi ilmiah ini.
Demikianlah terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
[right]Padang, 20 April 2004[/right]
[u]Daftar Kepustakaan[/u]
[u]Buku:[/u]
- Calin McAndrews, Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan, Raja Grafindo Persada Jakarta-1993
- Jeffrey A.Winters, Dosa-dosa Politik Orde Baru, Djambatan-Jakarta, 1999.
- Meriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia-Jakarta
- Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indoensia Suatu Model Pengantar, Sinar Baru-Bandung, 1988.
- Ichlasul Amal dan Reza Pangabean; Reformasi Sistem Multi Partai Dalam Rangka Peningkatan 1993
[u]Makalah[/u]
- Boy Yendra Tamin, Rekrutmen dan Model Pengisian Keanggotaan MPR, DPR (D) yang Demokratis dan Akuntabel, Jurnal Ilmu Hukum Jurisprudentia-Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Volume I No.2 Januari 2002.
- ----------------------, Makalah dalam Worshop Bagi Anggota DPRD Kab. Tebo Prov.Jambi, Padang, 2004.
- Indosman, Kedaulatan Rakyat dan Implementasinya di Indonesia, Pro Justitia, Tahun XII Nomor 4, Oktober 1994
[u]Artikel:[/u]
- Bara Hasibuan, Kompas, 30 Mei 2002
- Beni K. Harman, Kompas, 21/10/00.
- Bima Arya Sugiarto, Menuju Institusionalisasi Politik, Kompas-11 Januari 2001
- Ignas Kleden, Kebangkrutan Moral - Atau Ketakutan Politik?, Kompas, 24/01/02
- Indra J Piliang, Kompas 9 November 2000).
- Kuntjara Jakti dalam Syarif Hidayat, Persoalan Mendasar Implementasi Otonomi Daerah, Media Indonesia - 2/23/00.
- Makmur Keliat ââ¬Å Demokrasi Rapuhââ¬Â, Kompas 4 Januari 2001
- Mustofa Bisri, Kepentingan, Kompas 15 Maret 2002.
- Syarif Hidayat, Persoalan Mendasar Implementasi Otonomi Daerah, Media Indonesia - 2/23/00.
[u]Peraturan Perundang-Undangan:[/u]
- UU Nomor 3 Tahun 1999
- UU Nomor 12 Tahun 2003
Orasi Ilmiah ini disampaikan Boy Yendra Tamin, SH.MH dalam acara Dies Natalies ke 23 Universitas Bung Hatta 20 April 2004